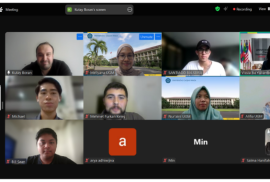Yogyakarta, 3 Juni 2025 — CESASS Talk Series #5 diselenggarakan secara daring, menghadirkan Dr. Tufan Kutay Boran dari Department of Area Studies, Social Sciences University of Ankara, Türkiye, yang membawakan presentasi berjudul “How Indonesian Political Parties and Islamic Organizations Influence Foreign Policy Making”. Sesi ini dimoderatori oleh Dr. phil. Vissia Ita Yulianto, yang memandu jalannya diskusi dan sesi tanya jawab bersama para peserta dari berbagai latar belakang akademik, termasuk para peneliti muda internasional.
SEA Talk_ind
[Yogyakarta, 29 September 2023] — Pada Rabu, 27 September 2023, Center for Southeast Asian Social Studies (CESASS) Universitas Gadjah Mada menyelenggarakan CESASS Talk Series 2, Bagian 2: “Narasi dan Konstruksi Identitas ASEAN”. Seminar hibrida ini menghadirkan diplomat Indonesia, Monica Ari Wijayanti, M.A., perwakilan dari Direktorat Kerja Sama Sosial-Budaya ASEAN, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.
Seminar ini membahas secara mendalam dinamika identitas ASEAN dan signifikansinya dalam lanskap global yang terus berkembang. Berikut beberapa poin penting dari acara tersebut:
Pada tanggal 20 Desember 2022 pukul 10.00 WIB, PSSAT (Pusat Studi Sosial Asia Tenggara) Universitas Gadjah Mada menyelenggarakan seminar dalam jaringan (online) dengan tajuk kegiatan South East Asia Talk (SEA Talk) edisi ke-46. SEA Talk #46 menghadirkan Bapak Made Supriatma, salah satu visiting fellow di ISEAS – Yusof Ishak Institute, Singapura, dengan bahasan berjudul “Dividing The Electorates: Will Indonesian Politicians Exploit Identity in 2024 Election”.
Kegiatan membahas seputar peran identitas yang melekat pada tiap individu dan potensinya dalam menggiring & menentukan pilihan individu tersebut dalam praktik penunaian tanggung jawab demokrasi, spesifiknya dalam pemilihan umum (pemilu). Indonesia yang lanskap sosial budayanya plural pun tidak luput dari penggunaan narasi identitas selama kampanye kegiatan pemilu.
“Di era ini, dimana penggunaan digital telah menjadi masif, akses yang mudah ke internet menjadi hal penting bagi semua orang termasuk anak-anak. Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk melindungi anak-anak mereka dari pedang bermata dua internet, yang meskipun begitu banyak manfaat yang ditawarkan, juga membuat mereka terpapar pada beberapa hal yang merugikan”, kata Nobertus R. Santoso, dosen ilmu komunikasi di Universitas Atma Jaya Yogyakarta pada rangkaian webinar South East Asia Talk (SEA TALK) ke-45, yang diselenggarakan oleh Center for Southeast Asian Social Studies (CESASS), Universitas Gadjah Mada
Center for Southeast Asian Social Studies Universitas Gadjah Mada mengadakan diskusi panel bertajuk SEA Talk #44 yang diselenggarakan pada tanggal 10 Maret 2022. Secara umum, CESASS UGM memiliki kepedulian terhadap sosial, ekonomi, politik, dan isu-isu budaya di kawasan Asia Tenggara sebagaimana disampaikan dalam diskusi panel. Dalam pembicaraan SEA Talk #44 ini, Prof. Dr. phil. Hermin Indah Wahyuni, S.IP, M.Si. selaku ketua CESASS UGM membuka dan menyambut peserta dan pembicara yang telah bergabung dan berpartisipasi dalam diskusi panel SEA Talk #44. Pembicara akan dibawakan oleh Drs. Moh. Arif Rokhman, M.Hum. Ph.D., yang merupakan Dosen Sastra Inggris Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada.
Pendidikan berfungsi sebagai instrumen yang dapat digunakan untuk memfasilitasi proses integrasi generasi yang lebih muda ke dalam sistem logika dan pengetahuan saat ini. Pendidikan juga berperan dalam membawa konformitas dan praktik kebebasan dimana individu dihadapkan pada realitas kritis dan kreatif dalam menemukan cara untuk berparitispasi dalam transformasi dunia mereka. Hal tersebut Prof. Alberto Gomes sampaikan dengan merujuk pada ide dan gagasan Virilio mengenai pedagogis kritis. Penyampaian ini merupakan salah satu penggalan dari Prof. Alberto pada seri SEA TALK ke #43 tentang bagaimana pentingnya pendidikan kritis. Prof. Alberto merupakan direktur pendiri dialogue, emphatic, engagement, and peacebuilding atau yang dikenal dengan DEEP Network dan juga selaku sebagai professor di Universitas Emiritus La Trobe, Melbourne, Australia. Dalam diskusi SEA Talk kali ini Prof. Alberto membawakan diskusi mengenai usaha emansipasi pembebasan pikiran yang terbelenggu melalui proses pendidikan kritis.
Bertujuan untuk parlemen abad ke-21
Ada kebutuhan akan sistem parlemen di Indonesia , Malaysia, dan Singapura untuk menjadi “parlemen yang berjalan”, dan demi mengatasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDG, mulai dari Sidang Pleno, sebagai wajah publik, Dr. Ratih D. Adiputri, dari Universitas Jyväskylä, Finlandia berkata di Southeast Asia Talk forum (25/05/2021). Ia mempresentasikan tentang sebuah bab yang berjudul Social Science Research in Southeast Asia: The Challenges of Study Parliamentary Institutions dalam diskusi seri buku “Social Science in the Age of Transformation and Disruption: Its Relevance, Role, and Challenge” (2020), diedit oleh Prof. Dr. phil. Hermin Indah Wahyuni dan Dr. phil. Visia Ita Yulianto dari CESASS, Pusat Studi Sosial Asia Tenggara, Universitas Gadjah Mada (UGM).
“Penelitian Ilmu Sosial hampir tidak objektif dalam mempelajari subjek yang diketahui dan selalu subjektif dalam beberapa hal”, kata Melanie V. Nerzt dan Vissia Ita Yulianto, penulis bab buku “Shifting Positionalities: The Shades of being inside and outside in social Science Research” (2020).
Dengan memanfaatkan sebagian besar pengalaman dalam melakukan kerja samaran antropologis sebagai peneliti Indonesia dan Jerman di pulau Sulawesi dan Jawa, Indonesia, pada tahun 2010 dan 2011, Melanie dan Ita menjabarkan peran yang mereka ambil dan dianggap dalam berbagai konteks lapangan dan mengeksplorasi implikasi menjadi orang dalam dan peneliti luar.
Pusat Studi Sosial Asia Tenggara (PSSAT) UGM menggelar agenda rutin SEA TALK #31 “Digital Literacies of Indonesian Secondary Students: What Have We Learned” bersama Jayne C. Lammers, Ph.D (University of Rochester USA) dan Puji Astuti, Ph.D (UNNES). Presentasi penelitian pada jumat (07/02/2020) ini disambut antusias oleh para peserta dalam diskusi interaktif.
Pada diskusi bulanan ini, Lammers dan Puji memaparkan hasil penelitian terbaru mereka mengenai digital literasi dalam pembelajaran siswa SMP dan SMA. Penelitian dibawah program FULLBRIGHT dari pemerintah Amerika Serikat ini dimulai sejak bulan September 2019. Data didapat dari 618 responden, yaitu para siswa di 3 SMP dan 4 SMA kota dan kabupaten Semarang. Fokusnya yaitu pada pengajaran Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) dalam kelas. Dalam presentasinya, kedua peneliti tersebut menjelaskan bahwa penelitian diadakan dengan studi kasus kolektif penjelasan menggunakan metode campuran.
SEA Talk #26 “Indonesia-Austria Bilateral Relation” with Simon Gorski (University of Vienna) at CESASS UGM Library (18/09/19). Thank you for your participation and see you at our next event!